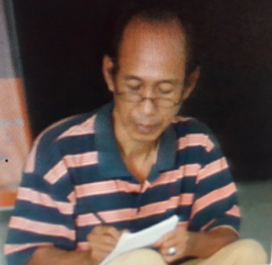Oleh O’ushj.dialambaqa*)
Membicarakan peradaban berarti pula membicarakan kebudayaan, karena perabadan berada dalam dunia kebudayaan. Untuk memperjelasnya kita mencoba untuk men-dua-kutub-kan hal tersebut.
Bukan berarti ada dua kutub yang terpisah antara peradaban dan kebudayaan. Pemisahan yang tersamar tersebut agar kita bisa memahami dua hal yang menyatu tersebut yang bisa terbaca dan terlihat pada dua hal yang seolah-olah berdiri sendiri, seolah-olah terlihat perbedaannya dengan jelas.
Melville Jean Herskovits-antropolog AS, penulis buku kontroversial “The Myth of the Negro Past”, mendefinisikan kebudayan adalah segala sesuatu yang diteruskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lain atau disebut superorganic, kebudayaan berisikan seluruh nilai, norma, pengertian, ilmu pengetahuan, religius, struktur, sistem sosial, dan nilai lainnya sebagai wujud budaya intelektual dan rasa seni yang menjadi identitas atau ciri khas suatu masyarakat. Sedangkan peradaban adalah nilai-nilai yang dihasilkan dari kebudayaan.
Oleh sebab itu, menjadi hal pondamental jika kita (Indramayu) ingin dilirik atau menjadi (pusat) perhatian publik luas, dan bahkan menjadi perbincangan dan kegelisahan warga dunia atau paling tidak, akan menjadi bagian dari sejarah dan waktu mengenai posisi kita ada, dan berada di mana dalam sejarah peradaban dan kebudayaan sebagai warga dunia.
Stigma Negatif Daerah
Stigma negatif dan atau gelap suatu daerah, khususnya Indramayu yang terkenal, dikenal dengan kawin cerai dan pelacuran intelektual, pelacuran akademik, dan yang lebih terkenal dengan Penjaja Sek Komersialnya (PSK), yang sedikit banyak telah berperan serta dalam perbaikan ekonomi keluarganya, akan tenggelam dengan sendirinya oleh apa yang hidup dalam daerah.
Kita bisa membangun peradaban dan budaya (kebudayaan) yang beradab, bermartabat, karena religiositas tidak bisa hanya menjadi jargon, slogan, retorika dan atau menjadi komoditas politis yang kemudian hanya membangun simbol-simbol politik identitas (terlebih keberagamaan), yang membuka ruang potensi benturan peradaban, dan bahkan menjadi candu bagi agama itu sendiri.
Stigma negatif yang menjadi fakta sosial-realitas empirik yang menjadi fakta sosiologis sejarah kita juga tidak bisa menafikkan itu semua. Akan tetapi, jika realitas emprik sebagai sebuah fakta sosial sebagai sebuah produk kebudayaan dan atau peradaban sejarah masa silam-masih terus hidup hingga kini, bukan berarti stigma negatif tersebut sebagai “harga mati” suatu daerah.
Akal budi religiositas yang akan menuntun keberakhir peradaban dan budaya tersebut, dari gelap bukan kembali lagi ke gelap, karena dalam kegelepan tersebut cahaya tak akan bernah padam menyinari akal budi atau pengetahuan manusia.
Tentu jika kita mau keluar (hijrah) dari takdir sosial menuju takdir sosial lainnya yang bercahaya, seperti dikatakan khalifah Umar bin Khottob saat semua umatnya, terutama Ubu Ubaisah-Gubernur Syam (yang mendebat soal wabah penyakit dan takdir), ingin tetap menembus wilayah bencana wabah penyakit yang amat sangat dahsyat di wilayah Saragih, di Lembah Tabuk-Negeri Syam.
Umar bin Khottob lantas memilih takdir sosial lainnya, dan menjelaskan pada umatnya. Mereka lantas melek situasi dan kondisi. Takdir sosial berada di tangan manusia itu sendiri. Selamatlah dari serangan wabah penyakit yang mematikan itu.
Berpindah menuju takdir sosial, tidaklah mudah dan tidaklah mungkin kita hanya “Menunggu Godot” yang diceritakan oleh Samuel Beckett, karena Godot adalah sebuah harapan atau pengharapan nun jauh yang harus kita berjuangkan sungguh-sungguh. Sisifus dan Danawa tak pernah ber-putus-asa memanggul batu berjalan mendaki, di mana batu-batu itu terus jatuh dan tak pernah sampai kependakian yang hendak dicapai.
Dalam memperjuangkan tatanan nilai tersebut, tentulah kita semua harus membuang jauh-jauh cara pandang dan analisis pasar-hukum ekenomi sebagai investasi yang harus diukur atau terukur dalam satuan nilai meteri atau terukur secara fiscal dan moneter, yang harus bisa tersajikan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Jika kita terbelenggu atau tertawan dalam cara pandang seperti itu, maka logika dan akal waras kita tersesat jauh dari akal budi. Tuhan dalam banyak hal tidak mengajarkan dan atau mengharuskan bahwa segala sesuatu harus tertakar secara materialistik dalam bentuk materi berwujud dalan satuan kertas yang bernilai dengan nama uang dan benda-benda lainnya yang harus dimaujudkan dalam bentuk materi fisikli.
Investasi pembangunan peradaban dan budaya merupakan investasi nilai-nilai peradaban dan kebudayaan yang bermatabat untuk menyelamatkan kesesatan cara pandang manusia, sehingga keterukuran atau parameter atau barometernya bukan pada meningkatnya PAD, tetapi prilaku sosial, pola pikir, cara pandang manusia yang akan menjadi fakta sosiologis suatu daerah yang terpelihara dalam kehidupan sosialnya.
Meski, bisa dipastikan multipler effectnya, bisa merajut pertumbuhan ekonomi secara signifikan..Akan tetapi, premis ini harus kita lempar jauh-jauh dulu pada saat mengkalkulasi untung rugi secara matematis materialistic (PAD/APBD). Jika itu terjadi, logika dan akal waras kita dilumpuhkan oleh sikap dan pandangan materiasm absolut-soak.
Peradaban dan Budaya
Ada banyak kalangan yang membedakan antara Peradaban dengan Budaya. Tidaklah salah jika pun kita kemudian patut memperhatikan perbedaan utama yang distabilo banyak kalangan tersebut, antara lain, yaitu:
- Istilah ‘budaya’ mengacu pada perwujudan cara kita berpikir, berperilaku dan bertindak. Sebaliknya, tahap peningkatan masyarakat manusia, di mana anggotanya memiliki cukup banyak organisasi dan pengembangan sosial dan politik disebut Peradaban.
- Budaya kita menggambarkan siapa kita, tetapi peradaban kita menjelaskan apa yang kita miliki atau apa yang kita gunakan.
- Budaya adalah tujuan; tidak memiliki standar pengukuran. Sebagai lawannya, peradaban memiliki standar pengukuran yang tepat, karena itu adalah sarana.
- Budaya daerah tertentu dapat tercermin dalam agama, seni, tari, sastra, adat, moral, musik, filsafat, dll. Di sisi lain, peradaban ditampilkan dalam hukum, administrasi, infrastruktur, arsitektur, pengaturan sosial, dll dari daerah itu.
- Budaya menunjukkan tingkat penyempurnaan batin terbesar, dan juga internal. Berbeda dengan peradaban yang bersifat eksternal, yakni perwujudan teknologi, produk, perangkat, infrastruktur canggih dan sebagainya.
- Perubahan dalam budaya diamati dengan waktu, seperti dalam pemikiran lama dan tradisi yang hilang dengan berlalunya waktu dan yang baru ditambahkan ke dalamnya yang kemudian ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Di sisi lain, peradaban terus maju, yaitu berbagai elemen peradaban seperti alat transportasi, komunikasi, dll berkembang dari hari ke hari.
- Budaya dapat berkembang dan berkembang, bahkan jika peradaban tidak ada. Sebaliknya, peradaban tidak dapat tumbuh dan eksis tanpa budaya.
Membangun Peradaban
Peradaban bukanlah monumental mati atau semacam fosil yang mensejarah, tetapi peradaban adalah denyut nadi yang tak pernah mati selama manusia masih hidup dan menjalani kehidupannya sebagaimana kata Tuhan bahwa kita semua adalah “khalifatullah fil ardh”, di mana kita sebagai “kholifah” dan kita sebagai “khilafah” yaitu peradaban umat menjadi tanggung jawab kita semua untuk ditata dan dipelihara.
Huntington mendefinisikan peradaban adalah suatu identitas terluas dari budaya, yang terindentifikasi bersama dalam unsur-unsur obyektif seperti bahasa, agama, sejarah, institusi, kebiasaan maupun melalui identifikasi diri yang subyektif.
Sebagai kholifah, kita mempunyai tanggung jawab moralitas secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan peradaban sebagai produk kebudayaan umat manusia.
Sebagai khilafah, kita yang dibebani dan diamanatkan oleh kebudayaan bertanggung jawab secara moralitas baik secara pribadi maupun kolektif, karena kita yang dalam sistem demokrasi (Trias Politika) menjadi pemegang amanat dan otoritas untuk menjalankan kedaulatan (dalam artian luas) untuk menciptakan dan atau mencapai kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, kemajuan, kemandirian dan hal-hal keduniawian dan hal-hal kerohanian kita.
Setiap saat Tuhan akan memanggil kita semua, yang dalam garamatika teologi dikatakan “kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun an ra’iyyatihi” (setiap manusia (orang, kamu, kita, kalian, saya-aku) adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya, dan dimintai pertanggung-jawabannya atas kepemimpinannya).
Peradaban tidaklah ansich, melainkan tak terpisahkan dari budaya (kebudayaan), sehingga dalam membangun peradaban, mau tidak mau, harus berjalan senafas, seirama, senada dengan budaya (kebudayaan). Keduanya bagaikan dua sisi mata koin dalam kehidupan umat manusia. Orchestra peradaban berbanding liniar dengan orchestra budaya (kebudayaan).
Maka, untuk membangun dua kutub orchestra tersebut harus juga lintas SARA (Suku-Agama-Ras dan Antargolongan), harus mengubur rasisme, karena jika dua kutub orchestra tersebut berjalan sendiri-sendiri, hanya akan melahirkan benturan peradaban, yang justru bisa menjadi bencana dan petaka, bukan lagi rahmatan lil’alamin (rahmat bagi semua umat).
Dalam peradaban, kita harus berakar pada pemahaman teologis dalam keberagamaan yang “lakum dinukum waliaddin” (agama-keyakinan-ku bukan urusan agama-keyakinan-mu atau urusanmu, dan agama-keyakinan-mu bukan pula urusan agama-keyakinan-ku atau urusan-ku).
Dalam pemahaman dan tafsir teologis yang lakum dinukum waliaddin, kita tidak lagi terjebak dan atau berkubang pada lumpur politik sektarian-identitas keberegamaan yang bisa memicu dan mengakibatkan genangan darah sepanjang sejarah peradaban umat manusia.
Pemahaman dan tafsir teologis tersebut dalam membangun peradaban dan budaya tidak akan melahirkan anak haram sejarah SARA atau tidak menjadi Si Malin Kundang peradaban itu sendiri. Karena peradaban yang akan lahir kemudian bukanlah berasal dari ‘vagina kekuasaan’ dan atau oligarki kekuasaan, bukan pula ‘janin peradaban’ yang akan lahir adalah berasal dari rahim vagina chauvinistik(isme) umat manusia.
Peradaban yang lahir adalah peradaban umat manusia yang sejuk, damai dan menjadi rahmatan lil ‘alamin dalam orchestra yang hidup sebagai panorama atau landskcap kehidupan umat manusia, di mana kita akan selalu berkaca pada air yang mengalir jernih.
Charles Kimball dalam When Riligion Becomes Evil menjelaskan, apakah agama menjadi masalah? Respon terhadap pertanyaan itu datang dari berbagai arah, dari masyarakat religius dan non religius sekaligus.
Kimball menjelaskan, sangat bergantung pada bagaimana orang itu memahami agama. Kemungkinan bahwa semangat keagamaan akan menghasut atau akan menjadi katalis kehancuran yang tak terperi bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Sejarah menunjukkan bahwa sejumlah pemimpin atau komunitas yang dimotivasi oleh semangat keagamaan dapat, dan bahkan ingin, melakukan tindak kekerasan dan teror atas nama Tuhan atau keyakinan mereka.
Konteks Chales Kimball tersebut berada dalam arena (gesekan, konflik sosial atau apapun namanya) kehidupan umat beragama dalam pratek keberagamaan atas eksistensi pluralisme agama dan keyakinan secara luas.
Akan tetapi, konteks itu bisa juga kita tarik ke dalam ruang yang lebih sempit, yaitu benturan peradaban yang disulut dan atau dibakar oleh persoalan budaya (kebudayaan), di mana kita memposisikan dirinya pada suatu titik tertentu yang kemudian ditarik menjadi suatu garis untuk dikonfrontatifkan baik secara horizontal mapun vertical ke dalam “ke-aku-an.” Kita menjadi atheis, pada akhirnya
Apa yang dikatakan Charles Kimball dalam gesekan sosial yang berakar dari persilangan teologis dan budaya (kebudayaan). Padahal, seolah-olah kita telah berpola pikir intelektual. “Cara berpikir intelektual dipengaruhi oleh kondisi yang melingkunginya dan situasi dan kondisi yang menelikungnya. Di sinilah mentalitas acapkali ambur-hancur lebur-terkubur dalam kesesatan.
Bahwa kekuatan intelektual terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang mengatur arena intelektual, dan karena itu, praktik mereka, adalah apa yang menjelaskan bahwa, secara kolektif seringkali di bawah suasana radikal, para intelegensia hampir selalu menyokong kekuasaan kelompok dominan.” (Pierre Bourdieu: Collective Intelectual).
Membangun Budaya
Seperti halnya peradaban, begitu juga dengan budaya (kebudayaan), bukanlah menjadi ke-ancsih-kan itu sendiri sebagai dua sisi mata koin. Oleh karenanya, budaya (kebudayaan) harus dibangun dan ditumbuhkan menjadi ladang atau kebun persemaian, sehingga akan hidup dan bermekaran. Seperti halnya dengan peradaban, budaya (kebudayaan) juga harus dibangun dengan pemahaman dan tafsir teologis yang tidak menyesatkan.
Untuk itu, kontruksi monumental budaya (kebudayaan) menjadi persoalan substansial, sehingga kita perlu juga belajar dan menarik pelajaran dari apa yang dilontarkan oleh Abu Hatim ar-Razi (saya tidak menggunakan terminologi kata memojokkan) terhadap Abu Bakr ar-Razi dengan pertanyaan, Saya (Abu Hatim ar-Razi dalam A’lam an-Nubuwwah) katakan: Apakah semua orang memiliki kadar intelektual, kemampuan memecahkan (persoalan), dan kepandaian yang sama, ataukah masing-masing berbeda?
Abu Bakar ar-Razi (dalam As-Sirah al-Falsafiyyah, Brion dalam “Philosophie et revelation”) menjelaskannya: “Jika mereka mau berupaya dan menyibukkan diri dengan apa yang dapat membantu mereka, maka mereka akan sama dalam hal intelektual dan pemecahan (persoalan). Tidak satu pun jiwa yang dapat lepaskan dari kekeruhan dunia itu dan lari ke masa depan, kecuali dengan filsafat kontemplasi.
Jika seseorang merenungkan filsafat dan memahami sesuatu, sekalipun itu sangat kecil, maka jiwanya akan dipisahkan dari kekeruhan dan diselamatkan (darinya).” Ar-Razi mengajarkan kepada kita dengan pendekatan filsafat kontemplasi dalam melihat dan menyelesaikan persoalan, bukan dengan sentiment teologis atau budaya, etnis dan lainnya.
Maka, kita harus memilih jalan keluar dari takdir sosial pemikiran yang tertawan untuk hijrah ke takdir lain (pinjam rujukan pemikiran Umar bin Khottob) untuk masa datang, agar umat manusia selamat dan keluar dari pertikaian chauvinistik peradaban sepenjang sejarah.
Budaya (kebudayaan) yang dibangun harus bisa hidup lestari dan asri. Budaya (kebudayaan) itu harus memilih jalan lurus, meski harus berkelok-kelok dan terjal yang dikarenakan kita hingga kini masih setia memelihara politik sectarian, salah asuh, sehingga menjadi atmosfir tebal politik identitas ke-SARA-an-yang kental dengan chauvinistik.
Tetapi sekaligus juga, bukan berarti kita tengah membrangus ke-SARA-an dalam konteks Bhineka Tunggal Ika, karena dalam ke-bhineka-tunggal-ika-an, justru SARA sebagai identitas budaya.
Keberagamaan akan tetap bisa terpelihara dan hidup dengan sejuk, damai dan asri sebagai kodrat dan atau takdir sosial kehidupan kita, di mana umat manusia dilahirkan berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan.
Tidak ada yang lebih mulia dari suatu bangsa atau golong-golongan (warga dunia) dari suatu bangsa atau golongan-golongan lainnya dari golongan itu sendiri, terkecuali bagi bangsa dan atau golongan-golongan yang berprilaku sosial politik dalam kehidupannya mengikuti petunjuk ‘Ihdinasshirotol mustaqiem’ dalam “ke-bhineka-tunggal-ika-an” umat manusia di muka bumi.
Oleh kaerannya, kebudayaan juga harus mempu memecah kebatuan pemahaman dan tafsir kita sebagai khalifah dan kekhalifahan, dan kita sebagai khilafah dalam kekhilafahan dalam kehidupan umat manusia di muka bumi.
Dialektika intelektual menjadi tumbuh dan akan hidup dan mengalir dalam kejujuran. Pertikain budaya (kebudayaan) akan melahirkan proses kreatif berkebudayaan yang akan melahirkan peradaban yang ber-adab dan berkualitas, bukan untuk saling menikam dan mengubur hidup-hidup, karena teologi yang chauvinistic, keberagamaan yang chauvintistic dan berbudaya chauvinistic.
Padahal, waktu dan sejarah telah bicara dan yang akan bicara, dan berarti waktu dan sejarah pula yang akan menguburkannya, bukan karena kita; kekuasaan yang bersemayam dalam diri kita sendiri dalam kegelapan mata dan kalbu.
Budaya (kebudayaan) merupakan wahana literasi peradaban, dan berarti membangun budaya (kebudayaan) membangun kontruksi literasi masa lampau, kini dan masa datang.
Apa yang dikatakan Rene Descrates bahwa “Saya Berpikir Maka Saya Ada” bisa dimaknai dari dua sisi koin, yaitu bahwa karena berfikir kemudian menjadi ada, dan karena ada menjadi harus berpikir, sehingga (ke)budaya(an) akan melahirkan peradaban yang sublimatif antara gelap dan terang dan atau dikegelapan yang terang, ke-adab-an dan ke-martabat-an dalam kehidupan dan hubungan sosial.
Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan, kebudayaan merupakan manifestasi dari cara berfikir. Abdul Hadi W. M. (dalam “Sutan Takdir Alisyahbana (STA) dan Pemikiran Kebudayaannya”, Februari 26, 2008 pada 3:24 am) memperjelas STA sampai pada kesimpulan bahwa yang paling penting ialah soal etika dalam hubungannya dengan nilai-nilai.
Di dalam lingkait (konteks) ini, etika bisa dibaca sebagai etika, etos, keberadaban (civility) dan kebajikan (virtue). Hubungan etika dengan nilai, merupakan inti utama dari persoalan kebudayaan yang dijumpai dalam sejarah semua bangsa sepanjang zaman.
Manusia, sebagai pencipta kebudayaan, mempunyai kodrat ganda. Pada satu sisi ia adalah makhluk alam dan pada sisi lain ia adalah makhluk budi. Sebagai makhluk alam manusia itu tunduk kepada hukum alam yang menguasai kehidupan lahir dan jasmaninya.
Sedangkan sebagai makhluk budi ia dikuasai oleh hukum budi (Geist dalam bahasa Jerman, mind dalam bahasa Inggeris, buddhi dalam bahasa Sanskerta, al-`aql dalam bahasa Arab; penulis Melayu abad ke-16 seperti Hamzah Fansuri dan Bukhari al-Jauhari menggunakan kata ’akal-budi’ atau ’budi’ saja untuk pertama kali dalam bahasa Melayu).
Abdul Hadi W.M. memberikan catatan, dalam pengertian ini, kebudayaan hanya berkembang jika ada komunitas yang mendukung kebudayaan itu dan terdapat suasana komunikatif serta lingkungan yang ramah terhadap berbagai ide dan pemikiran yang berkembang.
Dalam “Al-Muqadimah” Ibn Khaldun berpendapat, bahwa kebudayaan ialah kondisi-kondisi kehidupan yang melebihi dari apa yang diperlukan. Kelebihan-kelebihan tersebut berbeda-beda sesuai tingkat kemewahan yang ada pada kondisi tersebut. Ibnu Klhaldun mengatkan kebudayaan dengan keberadaan negara, maka kebudayaan akan berkembang dengan mantap dan dengan dilandasi kebudayaan, maka negara mempunyai tujuan spiritual dan nilai-nilai selaras dengan cita rasa bangsa yang warga dari negara bersangkutan.
Oleh sebab itu, membangun beradaban berarti juga harus membangun ke(budaya)an, karena peradaban merupakan produk kebudayaan yang tak terpisahkan. Menjadi keniscayaan pulalah kita harus membangun infrastruktur arena (ruang) terbuka bagi keduanya, yaitu Taman Literasi Budaya (TLB) yang menjadi tanggung jawab Negara (Pemda) yang diamanatkan dalam UUD’45 dalam hal kebudayaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di dalamnya tak terpisahkan dengan peradaban.
Taman Literasi Budaya Di mana?
Dua kutub orchestra di muka, melahirkan pertanyaan, di manakah ruang itu meng-ada agar dua orchestra itu hidup, tumbuh dan berkembang menjadi impian semua umat manusia, sehingga kita setiap waktu bisa menjalin padu, asa dan imaji-imaji yang diperdengarkan oleh harmonisasi melodi kehidupan dalam suatu peradaban yang bercahaya, di mana cahaya tersebut menembus batas, menyinari langit-langit pemikiran umat manusia, di mana kita meng-ada.
Sebagaimana takdir sosial sebagai taman, di mana Taman Literasi Budaya (TLB) tersebut agar bisa tetap hidup sepanjang masa, kita perlu merawatnya dengan kesungguhan jiwa dan ketulusan hati.
Tanpa kesungguhan jiwa, TLB akan berumah di atas angin di ladang tandus, dan hanya menjadi fosil monumental yang beku dan mati. TLB, bukanlah tempat bersemedai atau tumbuh bercokolnya rumah-rumah keong dan rumah-rumah kardus para seniman salon, budayawan bunglon dan vampir-vampir intelektual.
TLB bukan tempat beronani dan bersetubuhan para akademik yang melacur dan atau tempat segala pelacuran logika dan akal waras, yang dikemudian hari hanya akan melahirkan janin-janin peradaban dan kebudayaan “Si Malin Kundang” sejarah dalam peradaban dan budaya itu sendiri.
Lantas di mankah posisi TLB dalam struktur kelembagaan? Jika kita mengacu sebagai bahan pembanding, maka TLB berada dalam struktur kelembagaan dalam Disbudpar (Dinas Budaya dan Parawisata) sebagai UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) seperti halnya Taman Budaya Yogyakarta sebagai UPTD Disbudpar dan atau bisa juga di liding sektor Disdikbud, atau apapun namanya, seperti Aset Daerah.
Dalam hal teknis dan manajemen, liding sector yang terkait tersebut, tidak bisa melakukan intervensi-mengintervensi kebijakan yang menelikung untuk kepentingan dominasi politik sectarian, yang kemudian mengerahkan preman, buzzar, influencer untuk menggiring dominasi politik sektarianya sebagaimana telah dijelaskan di muka.
APBD hanya menyediakan dan memfasilitasi infrastruktur dan beban perawatan hidupnya TLB dalam kerangka pembangunan character building (Pembangunan Manusia Seutuhnya), bukan dalam kerangka PAD. Sekalipun, tak akan terbantahkan, akan lahirnya multiplier effect ekonomi; pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor riil dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Mikro dan Kecil dibedakan sehingga menjadi rancu).
Sekaligus, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam sektor ekonomi makro, bisa menjadi daya pesona investor untuk berkontribusi terhadap kemajuan daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi di sektor makro pun akan menggeliat. Kedua pertumbuhan ekonomi tersebut tentu akan berimplikasi pada PAD dalam APBD baik langsung maupun tidak langsung.
Posisi area TLB yang secara landscape yang masih sangat memungkinkan (representatif) adalah berada dalam kawasan Dayung Bojongsari-Kota-Indramayu yang menyatu dengan area gedung Mutiara Bangsa, Water Park dan Rumah Bertuah- dianekdotkan menjadi Rumah Berhantu lantaran filosofinya yang rontok.
Pagar sepanjang tempat TLB yang luas dan panjang, untuk fasilitas proses kreatif mural, lukisan dinding-corat caret tulisan, yang setiap hari bisa berganti-ganti, bisa ditimpa setiap hari oleh siapapun yang mau mengekspresikan jiwa, perasaan dan pikirannya. Tidak ada hak monopoli, karena setiap mural oleh pelukisnya yang kreatif akan didokumentasikannya sendiri, sebelum ditimpa oleh yang lain keseokan harinya.
Rumah Bertuah-Rumah Berhantu dengan fasilitas kerata monorelnya, kini menjadi barang ronsokkan. Jika mau direvitalisasi sebagai rekreasi edukatif, kereta monorel harus ditata dan didesain ulang, dengan melintasi Dayung hingga ke depan Kantor Pos Pusat-peninggalan Belanda.
Kereta monorel melintasi di atas sungai Cimanok-kawasan Dayung hingga Kantor Pos Pusat, sehingga anak-anak bisa melihat fakta konkret secara langsung sebagai rekreasi yang edukatif. Anak-anak dengan kereta monorel bisa menyaksikan langsung kehidupan riil masyarakat dan deretan kuliner di sepanjang kali-sungai Cimanuk dari atas kereta monorel.
Dalam kawasan tersebut terhampar air (bekas arena dayung Porda 2003) yang cukup memadai untuk argumentasi filosofis terhadap keberadaan TLB dalam ruang literasi budaya yang lintas sekat dan lintas bayang-bayang yang menjadi bayangan diri yang utopis.
Dalam TLB, kita juga bisa melihat setiap saat-setiap hari, minggu atau bulanan, kesenian dan (ke)budaya(an) hidup seirama dengan peradaban. Bahkan tidak hanya yang berasal dari kearifan lokal saja, melainkan dari berbagai wilayah budaya bisa tertukar dan bisa kita lihat.
Selain produk atau bentuk-bentuk kesenian dan budaya, dalam TLB pun bisa kita lihat, simak dan kaji berbagai bentuk kegiatan “Dialektika Intelektual” atau “Dialektika Akademik” dengan model-model yang tidak harus terkungkung dalam keformalan seperti pada umumnya, seminar atau diskusi dalam ruang tertutup-gedung atau dalam ruang gelap-sembunyi-sembunyi merayap. Yang penuh kecurigaan dan dicurigai penguasa.
Dalam dialektika intelektual akademik, itu mengusung dan atau akan bicara pikiran-pikiran dan argumentasi-argumentasi logika dan akal waras dalam banyak hal, antara lain, sosial, ekonomi, politik, sastra, budaya, seni, agama, hukum, pendidikan, iptek, teologi, dan lain-lainnya dalam semua aspek kehidupan umat manusia.
Formatnya, bisa baik dalam bentuk bedah (kritik) buku, bedah pikiran dan argumentasi masalah dan atau persoalan berbangsa dan bernegara sebagai manusia dengan pikiran-pikiran yang tidak tertawan dan atau terpasung bayang-bayang atau kepentingan politik praktis atau politik sektarian. Tidak boleh dipakemkan dalam kemerdekaan berpikir. Biarkan tumbuh natural, sehingga menjadi realitas sosiologis yang jujur, tidak dalam kemunafikkan.
Dalam kawasan TLB, kita bisa melihat hidupnya pasar seni dari proses kreatif dari produk kebudayaan dan peradaban yang didesain sedemikian rupa sehingga nuansa seni menjadi spiritualitas kehidupan. Dalam TLB, setiap saat kita bisa berkaca pada air yang terhampar memanjang yang disapu riak angin dan matahari.
Dalam kawasan ini pula kita bisa melihat, bertukar literasi dan budaya, dan kita bisa melihat pula setiap saat; saban hari, minggu, bulan atau tahun kehidupan budaya warga dunia baik secara non formal maupun formal dalam bentuk seperti festival, parade, pagelaran, pementasan dan apaun namanya, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional bisa kita gelar secara rutinitas. Lintas SARA, lintas kebudayaan, lintas bangsa, karena kita adalah warga dunia.
Data seni budaya Disbudpar hingga Agustus 2020, (sangat rancu dalam pengkatogorian, klasifikasi), kesenian yang tercatat dikelompokan ke dalam: A. Kesenian (28 jenis): Sandiwara, Tarling, Wayang Kulit Purwa, Wayang Golek Cepak, Sintren, Kuda Lumping/Jaran Cecek, Berokan, Reog Bleknong, Tari Topeng, Tari Rudat, Tari Ronggeng Ketuk, Tari Terbang Randu Kentir, Tari Srimpi, Tanjidor, Reog/Bleknong, Genjring Akrobat, Topeng Galon, Brai, Qosidah, Marawis, Gamelan Renteng, Macapat/Pujanggaan, Hadroh/Genjringan, Tayuban, Manuk Dangdut, Organ Tunggal, Orkes Gambus, Band.
- Nilai-Nilai Budaya (15 jenis): Upacara Adat Ngarot; Durungan Macul, Durugan Tandur dan Durugan Ngoyos, Sedekah Bumi, Ngunjung, Mapag Tamba, Mapag Sri, Nadran. Baritan, Khitanan, Ngupat, Mimitu, Tindak Siti, Rasulan, Upacara Perkawinan, Tolak Bala dan Nape , dll. C. Permainan Tradisional (8 jenis): Sampyong, Dolanan Bocah Dermayu; Slepdur, Ula-Ula Kelabang dan Icip-Icip Turi, dll, Balap Pehchun, Rebutan, Engklekan, Congkak, Glatikan dan Egrang/Jangkungan. Kelompok, seni terbagi menjadi (8 kelompok): Seni Teater/Drama, Seni Sastra, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan Rakyat, Seni Pedalangan dan Seni Kontemporer.
Komunitas-komunitas seni dan budaya di muka jumlahnya (berdasarkan klaim orang per orang atau kelompok) sekitar 300-400san komunitas, sehingga dengan masing-masing komunitas kebagian tampil atau berkontribusi (tanpa pamrih) dalam TLB hanya berkesempatan sekali saja dalam setahun.
Hal tersebut, sebagai bentuk panggilan moralitas; padamu Negri kami berjanji, padamu Negri kami berbakti, padamu Negri kami mengabdi, bagimu Negri jiwa raga kami.
Tetapi, jika berhendak tampil dalam arena stage komersial, tentu bisa berkali-kali, karena dalam TLB juga tersedia sarana dan prasarana untuk itu semua seperti gedung Mutiara Bangsa dipakai untuk sarana komersial dalam banyak bentuk pagelaran atau pementasan atau pertunjukan atau apapun nama lainnya.
Keberadaan TLB harus bercermin atas kegagalan kehadiran DKI (Dewan Kesenian Indramayu) sebagai spektrum dan episentrum peradaban dan budaya dalam icon identitas, karena yang meng-ada kemudian menjadi perpanjangan tangan kepentingan, bukan penyambung lidah peradaban dan kebudayaan seperti yang kita gagas (penggas/idea awal O’ushj.dialambaqa dan penyair Ahmad Syubbanuddin Alwy (alm) pada tahun 1998-1999).
DKI tidak lebih sebagai tempat para birokrat kesenian dan kontraktor seni dan budaya, seniman dan budayawan salon untuk menadah APBD, sehingga menyingkirkan jauh-jauh pemikiran kebudayaan dan peradaban sebagaimana yang memang seharusnya menjadi ruh dalam nafas dan geraknya.
Dalam catatan sejarah dan waktu yang bicara, kini DKI bukan lagi khazanah peradaban dan budaya, melainkan alat kekuasaan (kepentingan) dari rezim ke rezim, menjadi pemuja kekuasaan dan atau menghamba kekuasaan politik dan politik kekuasaan. Sejarah buruk ini tidak boleh terulang di dalam TLB.
Begitu juga, sama halnya dengan Sekolah Unggulan dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baru yang kita gagas (saya- O’ushj.dialambaqa pada penghujung tahun 1999), gagasan idea tersebut dilontarkan dalam makalah (artikel untuk media) diskusi publik, tetapi pada implementasinya menjadi salah kaprah.
Sekolah Unggulan hanya dijadikan “Brand” nama Sekolah Unggulan sedangkan mutunya tidak menjadi unggulan. Begitu juga BUMD baru melahirkan PD. BWI (Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu) dengan salah kaprah dalam manajemen maupun business core-nya. DKI dan Sekolah Unggulan memilih takdir sosialnya menghamba pada kekuasaan politik dan atau kepentingan politik.
Di negeri di persimpangan jalan. dipersimpangan jalan ini pula kita saling mendesah hingga gelisah menjadi sunyi dan senyap, begitu seterusnya. kata-kata kini telah menjadi kekuasaan dan bahasa telah menjadi kuasa, maka pikiran-pikiran yang dinyatakan dari logika dan akal budi senantiasa membentur batok kepala para penyair salon, membentur tembok-tembok para akademisi yang melacur, membentur dinding-dinding vampir intelektual, membentur benteng-benteng para budayawan yang beronani-bermastrubasi, yang dari musim ke musim senantiasa berkerumun dalam lingkaran sumbu-sumbu kekuasaan sehingga telah menulikan pendengaran, dan akal budi pun telah ditinggalkan. (O’ushj.dialambaqa-Sajak/Puisi: Negeri Di Persimpangan Jalan).
Maka, tak ada yang luput/bahkan mimpi pun tak/tanah tanah tanah/beri aku puncak/untuk memulai berpijak! dan/mari berlari/pada diri kita/dan kembali menyimaknya/dengan keheranan Adam pada perjumpaan/pertama dengan dunia (Sutardji Calzoum Bachri: Sajak Nuh & Mari).*****
Singaraja, ‘20’24.
*)Penulis adalah Penyair, Peneliti sekaligus Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) dan Accountant Freelance, tinggal di Singaraja. Kontak: 0819 3116 4563. Email: jurnalepkspd@gmail.com.